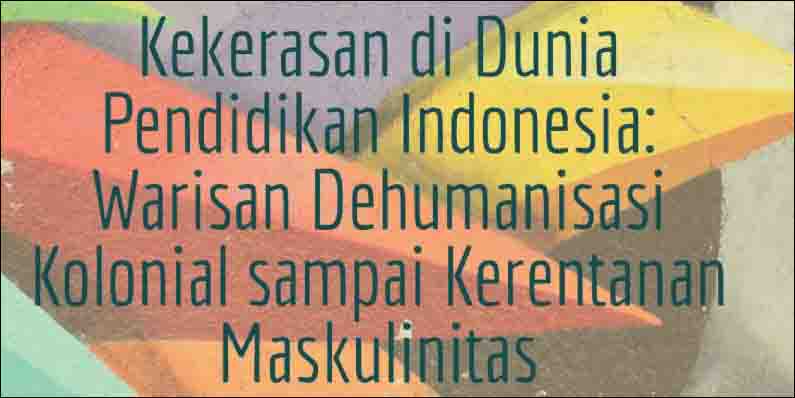Sutradara : Bong Joon H
Penulis : Bong Joon H, Jon Ronson
Aktor : Tilda Swinton (Lucy Mirando), Paul Dano (Jay), Seo-Hyun Ahn (Mija), Hee-Bong Byun (Heebong), Steven Yeun (K), Lily Collins (Red), Je-mun Yun (Mundo Park), Shirley Henderson (Jennifer), Daniel Henshall (Blond), Devon Bostick (Silver), Woo- sik Choi (Kim), Jake Gyllenhaal (Dr. Johnny Wilcox). Genre : Drama, Petualangan.
“Kulitnya yang kasar menyiratkan bahwa hidupnya yang keras tetapi alami. Tingkahnya tak sekasar penampilannya. Begitulah Okja… hubungan batin kita tidak akan mudah dipisahkan. Meski dengan emas atau permata kalian menukarnya, aku akan tetap mempertahankanya, Okja.”
Cuplikan puisi diatas merupakan refleksi singkat apa yang saya rasakan setelah menonton film berjudul Okja. Film yang di sutradarai oleh Bong Joon-Ho ini bercerita mengenai seorang gadis bernama Mija (Ahn Seo-hyun) yang tinggal bersama pamannya (Byun Hee-bong) sedari kecil. Mereka berdua tinggal di pegunungan yang jauh dari hingar binger perkotaan. Sejak umur 4 tahun, Mija memiliki hewan (sintetis) peliharaan yang bernama Okja. Hewan tersebut merupakan titipan dari perusahaan besar Amerika yaitu Miranda Corp untuk nantinya 10 tahun kedepan dapat diambil lagi dan diikutkan dalam kontes babi tercantik yang akan bersaing dengan 25 babi sintetis yang tersebar di 25 negara lainnya. Perusahaan ini bergerak dibidang pengembangan pangan hewan sintetis yang langsung di pimpin oleh Lucy (Tilda Swinton). Singkat cerita 10 tahun berlalu, perusahaan Miranda yang diwakilkan oleh Dr. Johnny Wilcox (Jake Gyllenhaal) untuk mengambil Okja dari tangan Mija agar dapat dibawa ke New York untuk mengikuti kontes. Kedekatan yang telah terjalin antara Mija dan Okja selama bertahun-tahun membuat Mija tidak serta merta melepaskan Okja begitu saja.
Berawal dari dibawanya Okja oleh orang-orang perusahaan Miranda inilah petualangan Mija dimulai. Mulai dari stasiun kereta bawah tanah di Korea Selatan sampai di kota New York. Perjuangan Mija untuk merebut Okja dari cengkeraman Miranda Corp ini tidak mudah dan diwarnai dengan drama. Selama perjalanan merebut Okja, ternyata Mija dibantu oleh sekelompok orang yang tergabung dalam From Pembebasan Hewan. Berkat bantuan merekalah Mija akhirnya bisa sampai di New York dan pada akhirnya bisa menyelematkan Okja. Namun dibalik kisah yang dramatis dan penuh petualangan ini ada beberapa realita yang coba digambarkan oleh sang sutradara.
Terlepas dari menariknya film Okja dari segi cerita dan sinematografi, terdapat fakta yang cukup mebuat mata saya terbelalak tentang kejamnya industry ternak modern. Film ini dengan sangat jelas menggambarkan tentang kekejaman manusia terhadap hewan ternak. Ada beberapa adegan yang menggambarkan kengerian industry peternakan modern dalam film tersebut. Adegan yang harus diperhatikan adalah ketika berada di laboratorium dan rumah potong milik Mirando Corp. Dalam adegan tersebut ditunjukan beberapa hasil hewan sintetis yang gagal dalam percobaan dan tak sesempurna Okja. Film Okja sebenarnya cukup jelas menggambarkan hal yang memicu munculnya bioteknologi untuk industry ternak modern. Salah satu pemicunya adalah untuk memenuhi permintaan dan ketersediaan pangan dari produk ternak. Sehingga banyak ilmuwan yang mencoba untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui bioteknologi.
Realita seperti ini yang mungkin terjadi di masyarakat kita. Bahkan tanpa kita perhatikan, sudah banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya ayam broiler, yang merupakan hasil perkawinan silang dengan system berkelanjutan hingga memperoleh mutu yang bagus seperti saat ini. Dengan pertumbuhan yang cepat inilah mempermudah manusia untuk menghasilkan daging dalam waktu yang lebih cepat pula dari ayam ternak alami.
Selain mengenai industri ternak yang dihasilkan oleh bioteknologi, satu lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang rumah potong. Di film Okja, rumah potong terlihat sangat brutal dan mengerikan. Di balik mewahnya daging yang tersaji di depan piring makan kita, terdapat proses yang keji, kejam, bahkan brutal. Seakan-akan hewan-hewan ini tak memiliki pilihan hidup selain berakhir dihadapan mesin pemotong yang akan mengakhiri nyawa mereka.
Dalam scene menjelang film berakhir ketika Mija ingin membebaskan Okja, terdapat adegan yang membuat kita sadar bahwa industrialisasi memang melegalkan segala cara demi kepentingan perusahaan, uang dan bisnis. Adegan ketika Mija memberikan babi emas untuk membeli Okja hidup-hidup menyadarkan kita bahwa harta telah menggantikan perasaan kemanusiaan diatas kepentingan bisnis. Membuang rasa kasih sayang kepada semua makhluk dan digantikan dengan ego kita terhadap kekayaan materi. Keegoisan di dalam diri kita membuat kita gelap mata terhadap perasaan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup.
Kontributor : Dwi Febrianto