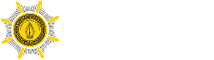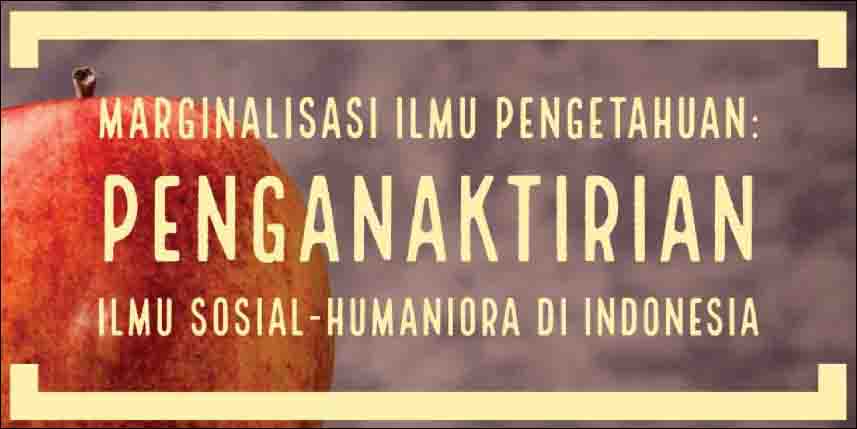PENGANAKTIRIAN ILMU SOSIAL-HUMANIORA DI INDONESIA
Polemik dikotomi ilmu sosial-humaniora versus ilmu sains-teknologi faktanya masih terus lestari hingga saat ini. Bagaimana para siswa yang memilih jurusan sosial-humaniora mengalami pengdiskreditan secara sosial dari masyarakat (terutama keluarga) bahkan negara. Masih cukup banyak orangtua yang merongrong anaknya untuk memilih jurusan teknik ataupun sains dengan alasan jurusan tersebut menjanjikan pekerjaan yang layak. Pihak sekolah dan para pendidik juga sering kali turut andil menjadi aktor utama dalam memperkeruh dikotomi ilmu dengan mengarahkan siswa dengan nilai rapor baik agar masuk jurusan eksak dan...